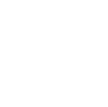Model Pemahaman Fiqih Muhammadiyah: Antara Salafiah, Mazhabiah dan Tajdidiah
Dibaca: 3113
Penulis : Prof. DR. Tgk. H. Al Yasa Abubakar, M.A.
PENDAHULUAN
Salah satu organisasi umat (Islam) yang sejak saat kelahirannya memproklamirkan diri sebagai organisasi tajdid adalah Muhammadiyah. Tajdid ini dirumuskan Muhammadiyah dalam dua sisi: paham keagamaan dan pengelolaan amal usaha. Dalam paham keagamaan, Muhammadiyah melakukannya dengan dua langkah, yang pertama berupaya kembali langsung kepada Al-qur’an dan sunnah, dalam arti tidak terikat kepada model pemahaman mazhabiah yang sudah ada. Kedua, kembali kepada Al-qur’an dan sunnah tersebut dilakukan tidak dengan mengikuti model pemahaman salafiah, tetapi dengan model lain (baru) yaitu model pemahaman (manhaj) tajdidiah atau pembaharuan. Dalam pemahaman awam selama ini, pemahaman keagamaan terkelompokkan hanya ke dalam dua model saja, mazhabiah atau bukan mazhabiah. Model mazhabiah mengikuti salah satu dari empat mazhab sunni yaitu: Hanafiah, Malikiah, Syafi`iah dan Hanabilah. Sedang model bukan mazhab, yang sering menyatakan diri sebagai kelompok yang ingin kembali kepada Al-qur’an dan sunnah secara langsung (maksudnya tidak melalui mazhab), sebenarnya adalah penguikut model salafiah, maksudnya mengikuti model pemahaman yang digunakan oleh para ulama sebelum kehadiran mazhab (ulama periode Sahabat dan tabi`in). Model salafiah sering juga dikatakan sebagai model sunnah yang menolak bid`ah. Mereka menganggap diri sebagai kelompok penegak sunnah dan anti bidah, kelompok yang berusaha kembali kepada Al-qur’an dan sunnah secara murni, yang tidak bercampur dengan bid`ah atau pikiran manusia. Sedang pengikut model mazhabiah kadang-kadang mengidentifikasi diri sebagai pengikut Ahlussunnawh al jama`ah, adalah kelompok yang mengikuti mazhab dalam pemahaman keaamannya. Mereka berisaha mengikuti ketentuan dalam mazhab dan merasa tidak boleh (tidak perlu) keluar dari ketentuan yang ada dalam mazhab karena yang ada dalam mazhab sudah dianggap memadai.
Jadi Muhammadiyah dalam paham keagamaannya menyatakan diri tidak terikat dengan model pemahaman mazhabiah dan juga tidak terikat dengan model pemahaman salafiah. Mereka mengajukan model baru yaitu model pemahaman tajdidiah. Di dalam berbagai dokumen, yang resmi dan tidak resmi, Muhammadiyah hampir selalu menyatakan diri sebagai persyarikatan (gerakan) yang kembali kepada Al-qur’an dan sunnah dan sekaligus juga sebagai gerakan tajdid. Anggaran Dasar tahun 2000, dalam Pasal 4 menyebutkan: (1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Ma`ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-qur’an dan As-Sunnah; (2) Muhammadiyah berasas Islam. Dengan demikian dalam diri Muhammadiyah melekat tiga ciri utama. Ciri pertama, merupakan substansi yaitu bersumber kepada Al-qur’an dan sunnah Rasulullah. Ciri yang kedua merupakan metode atau manhaj yang dipilih dalam upaya memahami dan mengamalkan Al-qur’an dan sunnah, yaitu model tajdidiah. Ketiga kegiatan dan amalan organisasi yang akan dilakukan yaitu dakwah yang berisi amar makruf nahi munkar.
Lebih dari itu, Haedar Nasir, salah seorang Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 dalam salah satu buku yang beliau tulis, mengutip beberapa tokoh yang telah meneliti Muhammadiyah, yang beliau kelompokkan menjadi empat: Kelompok pertama seperti Deliar Noer, James L Peacock dan William Shepard menggolongkan Muhammadiyah sebagai gerakan modern Islam atau modernisme Islam. Kelompok kedua, seperti Alfian dan Wertheim menggolongkan Muhammaadiyah ke dalam gerakan reformisme Islam. Kelompok ketiga, Abubakar Atjeh, menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan kembali kepada ajaran Salaf (Muhyi Atsari al Salaf). Kelompok keempat, seperti Clifford Geertz, George Kahin dan Robert van Neil, memasukkan Muhammadiyah ke dalam gerakan sosiokultural.[1] Menurut Haedar, semua penamaan dengan berbagai istilah tersebut memberikan substansi yang sama yaitu pembaruan atau tajdid. Selain dari pengakuan masyarakat luas ini, menurut Haedar, bukti substansial bahwa Muhammadiyah adalah gerakan tajdid (dalam paham keagamaan dan dalam pengelolaan amal usaha) dapat dirujuk paling kurang pada tiga hal: (a) percikan gagasan dasar Kiyai Haji Ahmad Dahlan selaku pendirinya; (b) pemikiran resmi yang dituangkan atau dilembagakan dalam organisasi; dan (c) dalam wujud karya amaliah dari pembaruan Muhammadiyah yang tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Di tempat yang lain, masih dalam buku yang sama, Haedar memberikan contoh pembaruan yang dilakukan KH Ahmad Dahlan di bidang karya amaliah yaitu: pertama, meluruskan arah kiblat, shalat hari raya di lapangan, serta menjauhkan praktik beragama dari syirik, tahayul, bid`ah dan khurafat. Kedua, pembinaan umat melalui pengajian-pengajian secara melembaga. Ketiga, memelopori pendirian sekolah Islam modern. Keempat, mendirikan PKU, Panti Asuhan dan pelayanan sosial. Kelima, mendirikan Taman Pustaka, Majalah Suara Muhammadiyah, dan lembaga penolong haji. Keenam, mendirikan `Aisyiah sebagai organisasi kaum perempuan.[2]
Tetapi apa makna dari istilah “tajdid (tajdidi, tajdidiah)” sebagai metode untuk memahami (kembali kepada) Al-qur’an dan sunnah, yang disebutkan di dalam berbagai dokumen resmi Muhammadiyah, ataupun di dalam tulisan para peneliti, serta bagaimana penerapannya di kalangan Muhammadiyah sendiri, baik dalam merumuskan ajaran dan pemikiran keagamaan, kelihatannya belum diuraikan dan dirumuskan secara jelas apalagi tegas. Dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah serta penelitian-penelitian tentang Muhammadiyah yang beredar luas dan sering dirujuk cenderung tidak menjelaskan beda antara tajdid (pembaharuan) dengan berbagai istilah lain yang digunakan oleh para peneliti tersebut. Buku Haedar pun tidak menguraikannya. Dengan demikian pengidentifikasian Muhammadiyah sebagai gerakan tajdidiah, salafiah, modernis atau reformis seharusnya diikuti dengan penjelasan yang memadai, sehingga umat mengetahui apa persamaan dan perbedaan semua istilah itu dan mana yang paling tepat untuk digunakan.
Sekiranya dikembalikan ke peristilahan yang digunakan oleh umat Islam, luas anggapan bahwa salaf (salafi, salafiah) dan tajdid (tajdidi, tajdidiah) adalah dua istilah yang berbeda, yang tidak sama maknanya. Namun seperti dikutip di atas, Abubakar Atjeh secara jelas menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan salaf. Bahkan selain beliau pun masih ada beberapa penulis lain yang menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan yang berupaya kembali kepada ajaran salaf atau bahkan menjadi pengikut salafiah. Berbeda dengan anggapan ini, AD Muhammadiyah, seperti telah dikutip di atas, menyatakan bahwa tajdid merupakan salah satu ciri bahkan mungkin merupakan ciri paling utama dari Muhammadiyah dan sama sekali tidak menyebut-nyebut salaf. Karena adanya ketidak-jelasan ini, sebagian pengamat, dan mungkin juga sebagian warganya, menganggap Muhammadiyah sebagai gerakan yang ingin kembali kepada Al-qur’an dan sunnah, yang diidentifikasi dengan dua metode: mengikuti cara-cara bahkan ajaran salafiah dan pada waktu bersamaan juga mengikuti cara-cara tajdidiah serta berusaha menghasilkan pemikiran yang bercorak tajdidiah (berupaya melakukan ijtihad). Dalam hubungan ini ada satu hal yang disepakati, Muhammadiyah tidak mengikuti mazhab atau paling kurang tidak berafiliasi dengan mazhab tertentu.
Di samping istilah tajdid dan salaf, di kalangan Muhammadiyah dikenal sebuah istilah lain yang berdekatan yaitu tarjih. Salah satu Majelis di lingkungan Muhammadiyah diberi nama Majelis Tarjih dan Tajdid. Di dalam kajian ushul fiqih istilah tarjih mempunyai makna yang relatif jelas yaitu sebuah metode yang berupaya memilih yang terkuat atau yang terbaik dari berbagai pendapat yang ada. Dikatakan memilih (mentarjih) yang terkuat kalau pemilihan tersebut dilakukan berdasar pertimbangan, mana yang paling dekat dengan maksud Al-qur’an dan sunnah Rasulullah atau mana hadis yang paling sahih dari berbagai hadis yang ada. Dikatakan memilih yang terbaik (paling maslahat) kalau pemilihan tersebut dilakukan atas pertimbangan mana yang paling lapang dan paling mudah untuk umat. Maksudnya ketika ada dua pendapat atau lebih berdasarkan dalil yang berbeda (yang semuanya memenuhi syarat), atau dua pendapat berdasarkan pemahaman yang berbeda atas sebuah dalil yang sama, maka akan dipilih mana yang paling lapang dan mudah untuk dilakukan atau mana yang paling membawa manfaat.
Tarjih (pemilihan) biasanya digunakan untuk kegiatan dan upaya memilih dari berbagai pendapat yang sudah ada. Kegiatan yang berupaya menghasilkan pemikiran baru (tajdid), apalagi yang sama sekali tidak berakar pada pendapat lama, tidak disebut atau tidak masuk ke dalam pengertian tarjih. Dengan demikian tidaklah terlalu berlebihan sekiranya dikatakan, bahwa kegiatan tarjih berada satu tingkat di bawah tajdid, dan mungkin karena itulah nama majelis ini menggabungkan kedua istilah tersebut, untuk lebih mengukuhkan bahwa Muhammadiyah betul-betul berupaya menjadi gerakan tajdid. Berupaya menjadi sebuah gerakan yang tidak ragu-ragu mencari dan menerima pemahaman baru atas Al-qur’an dan sunnah sekiranya pemahaman itu dianggap layak secara metodologi dan memberikan manfaat serta kemudahan yang lebih lapang kepada umat.
Sampai batas tertentu, terutama di kalangan awam, penyebutan Muhammadiyah sebagai gerakan yang berpaham atau mengikuti tajdidiah, atau tarjih bahkan dianggap termasuk ke dalam kelompok salafiah, dapat dianggap wajar, karena arti dari ketiga istilah tersebut tidak dijelaskan secara memadai. Tetapi kekeliruan tersebut tidak patut untuk dibiarkan terus berlanjut, karena secara ilmiah, ketiga istilah ini tidaklah sama. Menyamakan istilah-istilah di atas secara begitu saja, atau paling kurang menggabungkan semuanya sebagai paham atau aliran yang diikuti oleh sebuah organisasi atau orang perorangan, dapat dianggap mengandung kerancuan secara metodologis. Jadi perlu penjelasan kepada umat secara umum dan warga Muhammadiyah secara khusus, agar mereka memahami persamaan dan perbedaan isitlah-istilah di atas dan dapat menggunakannya secara relatif tepat.
Lebih dari itu istilah modernisme dan reformisme juga sebetulnya mempunyai makna yang tidak sama. Jadi penyebutan Muhammadiyah sebagai pengikut pemikiran (metode) tajdid dan salaf atau modernisme dan reformisme secara bersamaan, perlu diikuti penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan kebingungan dan kekeliruan.
Tulisan ini akan berupaya menjelaskan corak atau model berpikir umat Islam dalam upaya mereka memahami Al-qur’an dan sunnah, yang penulis bedakan menjadi salafiah (salafi), mazhabiah (mazhabi) dan tajdidiah (tajdidi). Tulisan ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu pendapat merupakan bagian dari pola salafiah, mazhabiah ataupun tajdidiah.
PENGERTIAN SALAFIAH, MAZHABIAH DAN TAJDIDIAH
Ada beberapa cara untuk memetakan (mengelompokkan) model atau corak berpikir umat Islam. `Abid al-Jabiri memetakannya menjadi bayani, burhani dan `irfani. Mulyadi Karthanegara menambahkan satu lagi, tajribi, sehingga menjadi empat model. Ada yang mengelompokkannya menjadi salafiah, mazhabiah, ishlahiah dan tajdidiah. Ada jugayang menggunakan model lain seperti tradisionalis, revivalis, reformis, dan modernis. Selain ini masih ada model-model lain, yang mungkin tidak perlu disebutkan. Penulis sendiri mengelompokkan pemikiran umat Islam—terutama sekali di bidang fiqih, menjadi tiga model atau corak: salafiah (salafi), mazhabiah (mazhabi) dan tajdidiah (tajdidi). Adapun ishlahiah tidak penulis masukkan dalam pembagian di atas karena penulis anggap tidak berdiri sendiri. Sebagiannya dapat dimasukkan ke dalam salafiah dan sebagiannya lagi dapat dimasukkan ke dalam mazhabiah. Tiga istilah inilah yang akan penulis uraikan di bawah.
Salafiah adalah model pemikiran yang mengikuti dan merujuk kepada cara berpikir yang dilakukan oleh para Sahabat Rasulullah (sesudah beliau wafat), yang kemudian diikuti lagi oleh tabi`in. Sahabat adalah orang yang setelah mereka masuk Islam sempat bertemu dengan Rasulullah; jadi dapat disebut sebagai generasi pertama umat Islam. Tabi`in adalah orang-orang yang setelah masuk Islam sempat bertemu dengan Sahabat; jadi mereka dapat disebut sebagai generasi umat Islam yang kedua.
Secara harfiah salaf berarti para pendahulu, generasi awal, yaitu generasi yang dipertentangkan dengan generasi yang datang belakangan (khalaf). Istilah ini pada awalnya digunakan untuk membedakan para generasi awal dengan generasi belakangan (khalaf). Generasi awal (salaf) adalah mereka yang di dalam hadis disebutkan sebagai orang-orang yang sangat setia dan tulus dalam mengikuti dan mematuhi tuntunan Nabi (as-salaf as-shalih).Mereka adalah generasi (orang-orang) yang mengetahui dan memahami ajaran Islam melalui metode internalisasi dan sosialisasi, yaitu cara belajar melalui pergaulan dan kehidupan sehari-hari, (mereka mendengar langsung tuntunan Nabi dan melihat langsung praktek yang dikerjakan Nabi). Setelah Rasulullah wafat, mereka cenderung bebas dan tidak terikat dengan model apapun (selain dari hati nurani, pikiran jerih dan ketaatan total mereka), dalam memahami ajaran yang disampaikan Nabi (termasuk ke dalamnya memahami Al-qur’an) dan praktek-praktek yang beliau contohkan dalam upaya mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di dalam sejarah mereka tidak dibatasi pada generasi Sahabat (generasi pertama, orang yang sempat bergaul dengan Nabi) saja, tetapi diperluas kepada generasi tabi`in. Generasi kedua ini dimasukkan ke dalam al-salaf al-shalih karena dianggap masih dapat mempelajari ajaran Islam melalui metode internalisasi dan sosialisasi karena mereka sempat hidup dan bergaul dengan Sahabat, sehingga mereka sempat melihat “bayangan” Rasulullah melalui praktek Sahabat. Setelah ini masih ada ulama yang memperluasnya, memasukkan sebagian orang dari generasi ketiga, (tabi` tabi`in)ke dalam kelompok al-salaf al-shalih dengan alasan sebagian dari generasi ketiga ini masih dapat melihat dan mengikuti jejak-jejak praktek Sahabat pada sebagian tabi`in. Kalau pandangan ini diterima, sebagian imam mazhab dapat dimasukkan ke dalam kelompok al-salaf al-shalih karena ada yang sempat bergaul dengan para Sahabat, sedang sebagian lagi sempat bergaul dengan tabi`in.
Adapun generasi belakangan (khalaf) adalah mereka yang tidak dapat lagi mengikuti dan menafsirkan ajaran yang disampaikan Nabi melalui metode intenalisasi dan sosialisasi (karena mereka tidak bertemu dengan Nabi). Mereka tidak dapat menafsirkan Al-qur’an secara bebas berdasarkan “kata hati dan pikiran jernih” yang diperoleh dari pengalaman hidup dan bergaul langsung dengan Rasulullah. Mereka harus menafsirkannya dengan metode dan model tertentu, menggunakan argumen, alasan, logika dan jalan pikiran yang dapat dijelaskan secara logis dan sistematis sehingga dapat diuji (diverifikasi).Menurut sebagian pengamat periode ini sudah dimulai oleh para ulama yang dianggap sebagai imam mazhab (pendiri mazhab), karena mereka dalam menjelaskan syariat sudah menggunakan model dan metode sistemais tertentu.Namun banyak juga ulama yang menyatakan baru dimulai dengan generasi sesudah imam mazhab, karena tidak semua imam mazhab menyusun dan menjelaskan metode penalarannya secara sitematis. Metode yang ditinggalkan imam mazhab baru menjadi sebuah model yang relatif sistematis dan padu, setelah disusun dan dirumuskan ulang oleh para ulama generasi berikutnya, yaitu mereka yang menjadi murid dan pengikut imam mazhab tersebut. Jadi baru para ulama generasi sesudah imam mazhablah yang menggunakan model dan metode tertentu dalam manafsirkan Al-qur’an dan hadis, atau lebih tepatnya mengikatkan diri kepada model dan metode imam mazhab masing-masing. Karena itu merekalah yang dianggap sebagai generasi khalaf pertama. Dengan demikian seperti telah disebutkan sebelumnya, istilah salaf pada awalnya dipertentangkan dengan khalaf, bukan dengan mazhab. Tetapi dengan perjalanan waktu, istilah khalaf tidak sering lagi digunakan,sudah digantikan dangan mazhab. Pada masa sekarang istilah pengikut salaf (salafi, salafiah) digunakan untuk menunjuk orang-orang yang menganggap diri mereka menjadi pengikut cara berpikir para Sahabat.
Sedang istilah pengikut mazhab (mazhabi, mazhabiah) digunakan untuk menunjuk mereka yang mengaku menjadi pengikut cara berpikir bahkan pendapat imam mazhab tertentu. Jadi mazhabiah adalah model pemikiran yang mengikuti dan merujuk kepada cara berpikir yang dilakukan oleh para ulama mazhab, yang muncul mulai paroh akhir abad pertama hijriah, di masa generasi ketiga sesudah Nabi Muhammad (yang paling tua mazhab Ibadhiah) dan terus berlanjut sampai awal abad keempat hijriah (mazhab Thabari atau Jariri, yang sekarang ini sudah tidak mempunyai pengikut lagi). Pada masa belakangan hasil pemikiran mereka dianggap sebagai model mazhabiah, sehingga orang yang mengaku pengikut mazhab dapat diartikan dengna salah satu dari dua makna: mengikuti hasil pemikiran yang dihasilkan oleh ulama mazhab, atau mengikuti metode dan cara berpikir yang ada di dalam mazhab. Dengan demikian pengikut salaf dan pengikut mazhab merupakan dua kelompok yang dapat dibedakan secara relatif jelas. Dengan demikian menggunakan istilah salafi atau salafiah untuk menunjuk mereka yang berafiliasi kepada mazhab tidaklah tepat, bahkan mungkin akan membingungkan umat.
Adapun tajdidiah adalah model pemikiran yang mengikuti dan merujuk kepada cara berpikir (dan hasil pemikiran) yang dipakai oleh para ulama kontemporer, yang berusaha keluar dari kedua model di atas. Jadi mereka berusaha melahirkan metode yang baru (ushul fiqih baru), dan setelah itu berupaya pula menghasilkan pemikiran yang relatif baru di bidang fiqih (dan bidang ajaran Islam lainnya). Mereka melakukan hal ini karena didorong oleh dua hal. Pertamakeadaan pada masa sekarang relatif sudah sangat berbeda dengan keadaan masa lalu, karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan yang telah melahirkan teknologi dan industri, yang pada masa lalu tidak ada bahkan tidak terbayangkan. Perubahan ini terjadi secara relatif mendasar dan menyeluruh, yang sering disebut sebagai perubahan paradigma. Kedua kemajuan dan perubahan pengetahuan dan teknologi tersebut telah menyebabkan berbagai perubahan di dalam masyarakat, yang pada giliran berikutnya menjadikan ketentuan yang ada dalam fiqih (mazhab dan salaf) tidak mampu lagi menampung semua perubahan tersebut. Karena itu para pendukung model tjadidiah berupaya melahirkan fiqih (hasil pemikiran) baru yang diharapkan akan lebih sesuai dengan keperluan masyarakatyang sudah sangat dipengaruhi oleh kemajuan ilmu dan teknologi.
Di pihak lain karena merupakan sesuatu yang baru, maka metode serta hasil pemikiran yang mereka hasilkan tersebut, sampai batas tertentu akan berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh kelompok salafiah dan mazhabiah. Keadaan ini sering menimbulkan keraguan bahkan kegamangan sampai kepada penolakan pada sebagian orang, karena apa yang mereka hasilkan dan ajarkan tidak mempunyai contoh pada masa lalu. Karena keadaan tersebut para pengikut model yang terakhir ini kadang-kadang tidak dapat menghindarkan diri dari tuduhan telah melakukan bid`ah atau telah keluar dan meninggalkan sunnah.
MODEL PEMAHAMAN SALAFIAH
Ciri utama pemikiran salafiah adalah sifat atau coraknya yang merupakan pemahaman atas Al-qur’an dan sunnah berdasarkan internalisasi atas nilai-nilai, sebagaimana mereka dapatkan dari hidup bersama Rasulullah, dalam masyarakat Arab abad ke tujuh masehi. Sahabat adalah generasi yang unik dalam sejarah Islam, karena merekalah satu-satunya generasi–sepanjang sejarah, yang hidup bersama Rasulullah. Mereka dapat memahami Islam melalui cara internalisasi dan sosialisasi, karena mereka telah bergaul dan hidup bersama Rasulullah dalam waktu yang relatif lama, yang tidak mungkin dilakukan oleh generasi manapun sesudah mereka. Ciri yang kedua, sebagai akibat dari ciri yang pertama, cenderung sederhana dan lapang, dalam arti mereka berupaya menyelesaikan masalah secara langsung menurut apa adanya; mereka tidak merasa perlu untuk memikirkan sebuah sistem (sistematika) untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Mereka hanya menggunakan logika sederhana katakanlah yang cenderung alamiah, bukan logika yang formal apalagi yag rumit. Mereka merasa cukup dengan pertimbangan nurani dan kata hati secara subjektif, karena mereka dipandu oleh nilai dan semangat Islami serta ketaatan kepada Rasulullah, yang sebelumnya sudah terbentuk melalui internalisasi dan sosialisasi. Ciri yang ketiga sebagai akibat dari yang kedua, para Sahabat cenderung berpikir praktis dan parsial (juz’iyyah) dalam arti mereka cenderung hanya berupaya menyelesaikan masalah kongkrit dan praktis yang mereka hadapi setelah masalah itu muncul. Dengan kata lain cenderung tidak memikirkannya sebagai bagian dari sebuah keseluruhan dalam sebuah sistem yang padu. Mereka tidka berusahamelihat atau mengembangkannya melalui sebuah sistem yang padu dan menyeluruh. Sejarah mencatat, mereka tidak ragu-ragu mengubah atau mengembangkan pendapatnya sekiranya ada alasan atau logika untuk mengubah pendapat lama tersebut, atau mereka menemukan alasan untuk membuat pendapat baru yang dianggap lebih baik dan maslahat, atau sesudah berdiskusi mereka menemukan contoh atau teladan dari Rasulullah yang berbeda dengan apa yang sebelumnya sudah mereka putuskan. Dengan demikian ketika pendapat tersebut dikumpulkan dan dibanding-bandingkan, ada yang menjadi tumpang tindih, bahkan saling bertolak belakang. Tetapi hal ini tidak menimbulkan kesulitan berarti di masa mereka, karena seperti telah disebutkan mereka menyelesaikannya kasus perkasus dan menerima perbedaan tersebut sebagai keragaman yang wajar.
Sekiranya kita kritisi, maka pemikiran (manhaj) salafiah mempunyai kelebihan dan kekurangan diantaranya sebagai berikut. Kelebihannya, mengikuti pendapat Sahabat akan memberikan kepuasan batin yang relatif tinggi karena ada hadis yang memuji dan mengunggulkan pemahaman para Sahabat. Salah sebuah hadis tersebut bermakna lebih kurang: Sahabatku seperti bintang di langit, yang mana saja kamu ikuti maka kamu akan mendapat petunjuk. Sebuah hadis yang lain bermakna lebih kurang: Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa’ur rasyidun (empat khalifah, yang ditunjuki) yang datang sesudahku. Kelebihan lainnya, pola pemahaman Sahabat cenderung sederhana, sehingga Islam terkesan mudah, dan lapang. Pemikiran para Sahabat yang diwariskan kepada kita sekarang, yang biasa dikutip di dalam buku-buku adalah aturan-aturan (hukum-hukum) yang berkaitan dengan persoalan keseharian umat, sehingga cenderung mudah dipahami dan mudah diikuti. Pemikiran yang sampai kepada kita tersebut, cenderung tidak ada yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan yang pelik atau kenegaraan yang multi dimensi.
Pada masa sekarang, para pengikut model ini pada umumnya merasa puas dengan pendekatan personal (mikro), kalau semua orang sudah baik maka masyarakat bahkan negara dengan sendirinya akan menjadi baik. Sekiranya buku yang ditulis pengikut salafiah masa sekarang diperhatikan, ada kecenderungan dan ajakan agar ajaran Islam tidak perlu ditafsirkan secara makro, tidak perlu sampai kepada memikirkan sistem ataupun model. Dalam hubungan dengan kepala negara misalnya, tugas umat hanyalah memilih orang yang baik dan cakap (memenuhi syarat). Sesudah itu beliaulah yang akan berijtihad dan menentukan kebijakan dan peraturan. Tidak perlu sistem ataupun pengawasan formal. Kalau petugasnya sudah baik tentu semuanya akan berjalan secara baik pula.
Dalam hubungan dengan mengikuti model ataupun kesimpulan yang dihasilkan para Sahabat melalai ijtihad mereka, ada persoalan penting yang harus dicermati. Sahabat adalah generasi yang di-Islamkan oleh Rasulul lah, yang sebelumnya hidup dalam adat Arab jahiliah. Sekiranya pendapat para Sahabat diperhatikan dan diteliti dengan baik, akan terlihat bahwa sebagian pendapat tersebut masih bersemangat jahiliah (keluar dari semangat Al-qur’an). Ketika Rasulullah hidup pendapat yang berisi semangat atau bahkan kecenderungan kembali ke adat jahiliah ini akan langsung beliau tegur dan perbaiki. Tetapi setelah Rasulullah wafat, ijtihad (pendapat) yang disusupi semangat jahiliah ini tidak dapat lagi dikonfirmasikan kepada beliau, dan karena itu tetap direkam sebagai pendapat Sahabat. Berhubung Sahabat telah diakui sebagai generasi yang unik, yang paling memahami ajaran Rasulullah, karena itu hasil ijtihad mereka dianggap sudah pasti benar bahkan paling benar, maka ijtihad mereka tidak perlu diragukan dan tidak perlu diuji (tidak boleh diuji). Dengan demikian ketika ada pemikiran mereka yang sebetulnya mengandung bias adat jahiliah, maka bias tersebut tidak akan dianggap sebagai penyimpangan, tetapi dianggap sebagai bagian dari sunnah Rasulullah dan cenderung diterima sebagai tafsir otentik atas Al-qur’an dan hadis. Imam mazhab pada umumnya menerima pendapat para Sahabat dan memasukkannya ke dalam pendapat mazhab mereka, tanpa memeriksanya apakah mengandung bias adat jahiliah atau tidak. Dengan demikian pendapat tersebut tetap berkembang dan tetap diterima sampai ke masa kita sekarang oleh mayoritas umat.
Untuk pernyataan di atas harus kita beri dua catatan. Pertama Sahabat adalah orang-orang yang sangat setia kepada Islam dan Rasulullah. Kalau mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan (putuskan) adalah penyimpangan dari ruh dan keinginan Al-qur’an, hampir dapat dipastikan mereka tidak akan melakukan ataupun mengikutinya. Tetapi ketika mereka tidak tahu (tidak merasa sebagai kesalahan) tentu maka mereka akan mengikutinya secara tidak sengaja atau tidak sadar dan untuk itu mereka tidak boleh disalahkan. Kedua, imam mazhab juga tidak dapat disalahkan ketika mereka menerima pendapat Sahabat yang pada masa sekarang dianggap mengandung bias adat jahiliah. Mereka harus dimaafkan karena pada mereka tidak ada metode atau perangkat yang dapat digunakan untuk menguji apakah pendapat tersebut mengandung bias adat jahiliah atau tidak. Kita pada masa sekarang relatif dapat mengetahui adanya kekeliruan atau pegaruh dari adat jahiliah yang harus ditinggalkan tersebut, adalah karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan. Kehadiran antropologi dan sosiologi misalnya, telah memungkinkan kita untuk membandingkan adat dalam masyarakat Arab dengan adat dalam masyarakat di berbagai belahan dunia, dan setelah itu memulangkannya kepada nash yang ada dalam Al-qur’an dan hadis. Dengan cara ini kita dapat mengetahui begaimana pengaruh adat Arab kepada tafsir yang diberikan oleh Sahabat.
Hal lain yang perlu diperhatikan, karena Sahabat melakukan penafsiran berdasar metode (model) internalisasi dan sosialisasi, maka model ini pada hakikatnya tidak dapat diikuti oleh generasi lain sesudah mereka. Tidak ada generasi sesudah Sahabat yang bertemu dengan Rasulullah, dan karena itu tidak ada lagi orang yang mungkin melakukan penalaran mengikuti model internalisasi dan sosialisasi. Umat Islam yang mengaku mengikuti para Sahabat (al-salaf al-shalih) di Nusantara sekarang, harus memilih salah satu dari dua hal. Pertama bertaqlid kepada pendapat Sahabat dalam arti mengikuti kesimpulan yang dibuat oleh para Sahabat menurut apa adanya, dan itu bermakna menenerapkan hasil ijtihad yang dirancang (oleh para Sahabat dan tabi`in) untuk masyarakat Arab abad ketujuh miladiah kepada masyarakat Nusantara di abad kedua puluh satu sekarang. Kedua mengikuti pola penalaran para Sahabat yang cenderung praktis, sederhana, lapang, terbukatetapi subjektif dan parsial, yang dipandu oleh kata hati dan pikiran jernih berdasar internalisasi dan sosialilasi tersebut. Tetapi karena model tersebut pada hakikatnya tidak mungkin diikuti, namun mereka memaksakan diri untuk mengikutinya, maka model tersebut berubah menjadi model penafsiran yang relatif harfiah dan hambar. Kadang-kadang menjadi sanagat longgar tetapi pada kesempatan yang lain menjadi sempit dan kaku. Para pengikut yang datang sesudah masa Sahabat (termasuk pengikut salafiah pada masa sekarang) kadang-kadang memahami nash secara literal, sehingga oleh para pengamat danggap sebagai kehilangan nilai. Kadang-kadang mereka lepaskan dari konteksnya, kadang-kadang mereka pahami secara terpotong-potong, dan kadang-kadang menakwilkannya secara subjektif dan serampangan, mereka sesuaikan dengan keadaan,pertimbangan dan keperluan kongkrit sesaat yang mereka hadapi (budaya serta adat mereka), tanpa pertimbangan yang sistematis dan komprehensif. Dengan demikian menurut sebagian pengamat, keputusan yang dikemukakan oleh para pengikut salafiah masa sekarang, mereka sadari atau tidak, ada yang sangat longgar atau sebaliknya sangat kaku dan sempit, sebagaimana ada yang sudah bersifat semena-mena, bahkan liar; sehingga sukar dibantah kalau ada yang menuduhnya sudah keluar dari ruh (semangat, nilai-nilai) syari`at.[3]
MODEL PEMAHAMAN MAZHABIAH
Model atau corak yang kedua adalah pemikiran mazhabiah. Sekiranya dibandingkan dengan fiqih hasil pemikiran para Sahabat, ada beberapa ciri yang membedakan keduanya yang dapat dicatat. Ciri pertama, para ulama mazhab berupaya menyusun fiqih mereka menjadi pemikiran yang relatif mencakup dan sistematis, sebagai ganti dari pemikiran yang juz`iah pada masa Sahabat dan tabi`in. Untuk itu para ulama mazhab berupaya membakukan peristilahan yang digunakan dan bahkan menyusunnya ke dalam kategori-kategori. Salah satu yang dirasa sangat penting adalah keberhasilan mereka menyusun hukum syara` ke dalam kategori hukum taklifi dan hukum wadh`i, serta pemisahan yang relatif jelas antara rukun dengan syarat. Mereka juga menyusun metode untuk mengistinbatkan fiqih (yang pada umumnya didominasi oleh metode lugawiah), yang bersama-sama dengan peristilahan di atas disebut ushul fiqih. Perbedaan metode dan sampai batas tertentu perbedaan kategori dan peristilahan inilah yang menjadi ciri, yang membedakan satu mazhab dengan mazhab lainnya. Begitu juga ketentuan-ketentuan fiqih mereka pilah-pilah dan mereka kelompokkan sehingga muncul sistematika pembagian fiqih menjadi bab (rubu`) ibadah, mu`amalah, munakahat dan jinayat. Memang harus kita catat, salah satu penyebab kelahiran mazhab adalah upaya untuk membakukan peristilahan dan mensistematisasi pendapat para Sahabat (salaf) yang saling tumpang tindih dan bahkan bertolak belakang, sehingga cenderung menimbulkan kebingungan dan bahkan kekacauan pada masa imam mazhab tersebut.
Ciri kedua, dalam upaya menyusun ketentuan-ketentuan agar menjadi sistematis seperti disebutkan di atas, mereka memilih pendapat-pendapat yang dihasilkan oleh para Sahabat tersebut dengan logika dan metode tertentu yang telah mereka susun, yang disebut ushul fiqih (ciri pertama tadi). Mereka berusaha memilih dan menguatkan salah satu dari banyak pendapat yang diberikan oleh para Sahabat dan mengabaikan selebihnya melalui metode yang telah mereka susun tersebut. Jadi pendapat yang relatif banyak dan beragama pada masa Sahabat tersebut oleh imam mazhab dipilih satu yang dianggap paling kuat atau yang paling maslahat, sesuai dengan metode yang mereka susun, sedang yang selebihnya mereka abaikan. Pada masa belakangan, di tangan para pengikut mazhab, pendapat Sahabat yang diabaikan,yang relatif masih banyak tersebut cenderung dilemahkan sampai ke tingkat ditolak. Dengan demikian disadari atau tidak kehadiran mazhab di satu segi menjadikan fiqih lebih sistematis dan logis, tetapi di pihak lain telah mempersempit keadaan lapang yang ditemukan dalam model atau pola para Sahabat (salafiah). Sepanjang bacaan penulis, imam mazhab tidak berupaya mencari pendapat baru selama masih ada pendapat Sahabat. Mereka hanya berupaya memilih salah satu dari berbagai pendapat Sahabat yang ada, dan mereka kelihatannya tidak berani meninggalkan atau keluar dari pendapat Sahabat tersebut.[4]
Ciri yang ketiga adalah keterikatan para imam mazhab dengan pendapat Sahabat. Fiqih mazhab ditegakkan di atas pendapat para Sahabat. Fiqih Sahabat yang disusun dengan metode internalisasi dan sosialisasi, disistematisasi oleh para imam mazhab dengan metode dan logika tertentu. Fiqih mazhab adalah seleksi sistematis atas fiqih yang disusun berdasar model pemahaman internalisasi dan sosialisasi. Jadi walaupun sudah sistematis, fiqih tersebut tetap bersifat parsial dan cenderung terlepas satu sama lain. Para pendudukng mazhab kelihatannya tidak berusaha menyusun fiqih yang parsial dan praktis, yang relatif sudah sistematis dan menyeluruh tersebut, menjadi fiqih yang secara ilmiah dapat disebut baku dan padu. Himpunan peraturan tersebut tidak menjadi himpunan yang sistematis, padu, menyatu dan menyeluruh secara akademik, tetapi merupakan sebuah himpunan yang sistematis dan menyeluruh namun pada hakikatnya masih tercerai berai, belum menjadi sesuatu yang padu dan menyatu.
Ciri yang keempat, karena berupaya menyusun fiqih secara sistematis dan menyeluruh, dengan metode istinbat dan peristilahan yang relatif sudah baku, maka mereka terdorong untuk melakukan ijtihad bukan saja untuk memecahkan masalah yang terjadi secara nyata di tengah masyarakat dan belum ada hukumnya, tetapi kadang-kadang berupaya juga untuk mengetahui hukum atas persoalan-persoalan yang belum terjadi tetapi mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga fiqih yang mereka susun sampai batas tertentu dapat dianggap lebih lengkap dari fiqh Sahabat (salafiah) dan juga berorientasi ke masa depan. Dengan demikian setelah memilih pendapat Sahabat, mereka mengisi bagian yang masih kosong dengan pendapat baru berdasarkan ijtihad mereka.
Ciri kelima di atas melahirkan ciri yang keenam yaitu, fiqih bergeser dari kegiatan untuk mencari tuntunan praktis guna membimbing umat memecahkan persoalan nyata yang mereka hadapi, menjadi semacam kegiatan ilmiah dan akademis, berupaya menafsirkan Al-qur’an dan sunnah menggunakan metode tertentu, untuk memperoleh berbagai kemungkinan yang secara formal dapat diterima, dan setelah itu menyusun hasilnya menjadi kitab-kitab fiqih yang dianggap mencakup dengan sistematika dan logika tertentu. Pada saat ini fiqih mulai kehilangan nilai sebagai pembimbing moral dan pemberi arah bagi kehidupan praktis. Kitab fiqih berubah menjadi himpunan berbagai pendapat yang diberikan para ulama, yang secara metodologis sudah dianggap memenuhi syarat dan karena itu dapat diikuti, walaupun sebagian daripadanya saling bertentangan dan bahkan bertolak belakang. Sering pendapat-pendapat tersebut merupakan berbagai kemungkinan yang dapat disimpulkan atas isi sebuah ayat atau hadis. Sering juga ketentuan-ketentuan fiqih tersebut berbentuk kemungkinan-kemungkinan (kesimpulan-kesimpulan) yang dapat diambil atas berbagai jalan pikiran yang dikemukakan di dalam diskusi-diskusi. Dengan demikian secara umum, tidaklah terlalu berlebih-lebihan sekiranya dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan fiqih tersebut telah berubah menjadi aturan atau tuntunan perilaku yang berisi hal-hal yang mungkin (boleh) untuk dilakukan, yang secara formal metodologis adalah benar, tetapi telah kering dari nilai moral dan hikmah yang ingin dituntunkan Al-qur’an, atau yang ingin dicapai dari pengamalan tersebut. Dengan kata lain, pencarian kebenaran (kemungkinan-kemungkinan) secara formal metodologis ini tidak diikuti dengan pencarian nilai moral dan hikmah yang terkandung di dalam nash Al-qur’an.
Setelah itu kitab-kitab tersebut diajarkan kepada para murid, melalui ruang belajar yang sebagiannya secara sistematis dan terencana, serta didiskusikan dan diperdebatkan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Kegiatan ini di samping untuk meningkatkan pengetahuan, dimaksudkan juga untuk mengetahui keunggulan dan kelemahannya sekiranya dibandingkan dengan mazhab-mazhab lain, yang secara umum dianggap sebagai saingan. Lebih dari itu bahan yang ada itu juga diupayakan untuk diperluas dan dikembangkan secara deduktif, sehingga isi kitab fiqih mencakup masalah-masalah atau kemungkinan-kemungkinan yang hanya ada dalam pikiran, yang tidak akan ditemukan secara nyata di tangah masyarakat (masalah iftiradiyyat). Jadi kalau sebelumnya nilai praktis dan kemampuan memecahkan masalahnya (memberikan kemanfaatan dan kelapangan) yang sangat menonjol, maka sesudah kelahiran mazhab secara perlahan bergeser kepada menonjolkan nilai polemis, untnuk mencari kebenaran formal sesuai dengan garis yang sudah ditentukan di dalam mazhab. Dengan perjalanan waktu, ketentuan dan pembahasan yang ada dalam kitab-kitab fiqih lebih banyak digunakan sebagai bahan untuk mengasah pemikiran di dalam diskusi-diskusi dan membela mazhab, daripada untuk panduan praktis dalam upaya meningkatkan kualitas pemahaman dan memberikan kelapangan kepada umat dalam hidup keseharian mereka.
Ciri ketujuh, karena dianggap telah mencakup (sampai kepada membahas masalah yang hanya ada sebagai kemungkinan-kemungkinan), telah dituliskan ke dalam kitab-kitab secara relatif sistematis dengan metode yang juga relatif jelas, dan lebih dari itu diajarkan pula secara sistematis dan terencana, maka mudah sekali mengundang pengkultusan terhadap imam yang melahirkannya. Di dalam kenyataan secara beangsur-angsur, pemikiran mazhab menjadi tertutup bahkan terhenti; para penerus mazhab tidak mampu berorientasi ke depan, sebaliknya berorientasi ke belakang, merasa puas dengan fiqih yang dihasilkan imam mazhab, cenderung mengkultuskan dengan cara menjadikan pendapat mazhab sebagai kebenaran yang tidak dapat ditandingi lagi, menjadi semacam “ideologi bahkan dogma” yang harus dibela dan dipertahankan.
Pemikiran (manhaj) mazhabiah sekiranya dikritisi, juga mempunyai kelebihan dan kekurangan diantaranya sebagai berikut. Kelebihannya, mengikuti pendapat mazhab dapat memberikan kepuasan karena dianggap mengikuti pemikiran para ulama, yang kualitas pengetahuan dan keimanannya sangat dihormati dan lebih dari itu telah tersusun secara relatif lengkap dan rapi. Mengikuti mazhab juga memberikan semacam kemudahan, menjadikan pengikutnya tidak perlu berpikir, cukup mencari ke dalam kitab-kitab. Apa yang ada dalam kitab mazhab relatif telah dianggap lengkap dan telah tersistematisasi. Bahkan ada ulama pengikut mazhab yang sampai pada keyakinan, bahwa pendapat yang ada dalam mazhab telah menjawab semua masalah, generasi (masa) ijtihad sudah berakhir dan umat tinggal bertaqlid saja. Jadi generasi yang datang sesudah imam dan ulama pengembang mazhab, cukup sekedar memilih dan mengamalkan apa yang ada dalam mazhab, tidak perlu (dan ada yang berpendapat tidak boleh) lagi mencari atau memikirkannya. Dengan demikian orientasi ke masa lalu akan terasa kuat sekali. Fiqih menjadi beku, diajarkan sebagai materi yang sudah selesai, sekedar untuk dipahami, dihafal, dilaksanakan dan setelah itu diajarkan kembali.
Keadaan ini secara perlahan-lahan menjadikan fiqih (mazhab) terpisah dari kehidupan nyata masyarakat. Fiqih dipelajari terutama untuk mengetahui bagaimana ketentuan yang ada di dalam kitab fiqih (apa yang mungkin distinbatkan dari sebuah dalil), sedang kesesuaiannya dengan keperluan dan keadaan di dalam masyarakat sering tidak menjadi pertimbangan lagi. Secara agak berlebih-lebihan, dapat disebutkan fiqih menjadi semacam fosil, tidak mampu menjalankan fungsi perlindungan, apalagi pencerahan dan pembebasan. Dalam keadaan tertentu, untuk menyiasati keperluan nyata di tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam mazhab, para ulama melakukan penyesuaian dengan membuathilah, atau malah meninggalkan fiqih sama sekali. Hilah adalah upaya merekayasa ketentuan fiqih yang ada sehingga suatu perbuatan yang secara hakiki tidak sesuai dengan fiqih, tetapi dengan melewati formalitas tertentu maka perbuatan tersebut dianggap telah sesuai dengan fiqih, paling kurang secara formal. Di pihak lain, karena ketentuan yang ada di dalam kitab fiqih dianggap sudah lengkap dan sempurna, maka masalah yang tidak ada ketentuannya di dalam fiqih cenderung dianggap sebagai bukan masalah fiqih dan karena itu berada di luar fiqih. Karena itu pengikut mazhab sering tidak peduli atau paling kurang merasa tidak terpanggil untuk membahas dan memecahkan masalah-masalah yang tidak dibahas di dalam fiqih. Mereka merasa puas dengan sekedar mengutip atau mengulangi apa yang sudah ada, dan sudah di bahas di dalam fiqih. Sebagai contoh, zakat dibatasi hanya pada jenis tanaman tertentu (misalnya padi), sedang jenis tanaman lain yang tidak disebutkan di dalam kitab fiqih (misalnya kelapa sawit, kopi atau cengkeh), dianggap tidak kena zakat walaupun tanaman yang terakhir ini memberikan penghasilan yang besar dan menjadikan petaninya lebih kaya dari petani jenis tanaman pertama. Begitu juga banyak pihak menolak adanya kewajiban zakat atas penghasilan dari sektor jasa, karena tidak diatur oleh mazhab, walaupun pada masa sekarang banyak orang yang bekerja dan menjadi kaya dengan penghasilan dari sektor jasa. Dengan demikian, alih-alih menjaga masyarakat agar tetap islami, mengupayakan masyarakat agar tetap hidup dalam tuntuan dan perlindungan fiqih secara menyeluruh (fiqih anggap meliputi semua perbuatan dan keperluan manusia), pola mazhabiah secara langsung atau tidak mendorong kehadiran dualisme hukum di tengah masyarakat. Bagi pengikut mazhab yang fanatik (ekstrim), perbuatan dan kegiatan yang tidak ditentukan hukumnya di dalam mazhab tidak termasuk perbuatan yang harus dicarikan hukum fiqihnya karena berada di luar lingkup fiqih. Perbuatan-perbuatan tersebut boleh bahkan harus diatur oleh hukum sekuler, karena tidak akan diatur oleh hukum fiqih.
Masalah lainnya, karena berupaya mencari kebenaran tunggal, maka kecenderungan untuk mengkultuskan, dalam arti mengagungkan mazhab sendiri serta merendahkan bahkan menyalahkan mazhab lain, cenderung tidak dapat dihindari yang pada akhirnya sampai ke tingkat menyebabkan pertengkaran serta perpecahan berkelanjutan di tengah masyarakat.
Keadaan ini boleh dikatakan mencapai puncaknya dengan terjadinya pembagian jemaah shalat fardhu di Masjid Haram berdasarkan mazhab. Sejak akhir abad kelima hijrah, sekitar masa Imam Ghazali, shalat berjamaah di Masjid Haram dilakukan empat kali berturut-turut oleh empat jamaah yang berbeda sesuai dengan mazhab masing-asing. Pertama sekali sesudah azan di awal waktu dilakukan shalat berjamaah oleh kaum muslimin bermazhab Syafi`i dan Hanabilah (dua mazhab ini bergabung dengan seorang imam), lalu Hanafi, lalu Maliki, dan terakhir jemaah bermazhab Syi`ah.[5] Sedang shalat Maghrib, karena waktu yang relatif pendek, maka semua mazhab menunaikannya pada waktu bersamaan. Jadi ada empat jamaah umat Islam, yang menunaikan shalat fardhu secara bersamaan, dengan empat imam yang berbeda berdasarkan dengan mazhab di dalam Masjid Haram. Karena berdekatan, dan semuanya membaca (memberi komando, memakai muballigh) dengan suara yang keras, maka suara imam yang satu sukar dibedakan dengan suara imam yang lain, sehingga ada jamaah yang mengikuti komando dari orang yang bukan imamnya. Buku-buku kisah perjalanan menceritakan bahwa pada shalat Maghrib selalu terlihat kesemrawutan, banyak jamaah yang melakukan gerakan yang keliru, karena mereka mengikuti imam dari jamaah yang lain. Perbedaan imam ini menimbulkan pengelompokan jamaah di dalam masjid yang relatif tajam, masing-masing pengikut mazhab mencari tempat duduk di tempat yang sudah dikhususkan untuk mereka, sehingga tidak terjadi perbauran antar sesama umat.[6]
Keadaan ini berlangung selama berabad-abad dan baru berakhir setelah Raja Abdul Aziz bin Sa`ud merebut Makkah pada tahun 1926, dan menyuruh semua umat Islam melakukan shalat fardhu di Masjid Haram dan Masjid Nabawi di Madinah masing-masing dengan seorang imam.
MODEL PEMAHAMAN TAJDIDIAH
Secara harfiah tajdid berarti pembaharuan. Istilah ini tidak asing dalam khazanah pemikiran Islam, karena ada sebuah hadis yang menyatakan bawa setiap seratus tahun akan lahir ulama pembaharu (mujaddid) di kalangan umat Islam. Umat Islam memahami tajdid (pembaharuan) atas Islam sebagai pembaharuan pemahaman (tajdid al-fikr al-dini). Maksudnya pembaharuan pemahaman atas Al-qur’an dan sunnah Rasulullah. Al-qur’an sendiri tidak mungkin dan tidak akan diperbaharui, karena Al-qur’an adalah wahyu yang keberadaan dan kebenarannya bersifat mutlak (absolut), yang tentang hal itu tidak ada diskusi lagi. Dalam khazanah fiqih sendiri ada sebuah prinsip mengenai pembaharuan yang sdah sangat ikenal, al-muhafazhah `ala-l qadim-ish shalih wa-l akhdzu bi-l jadid-il ashlah. Maksudnya, hasil pemikiran masa lalu akan dipertahankan sepanjang dianggap relevan dan masih bermanfaat. Namun sekiranya dapat dihasilkan pemikiran baru yang lebih baik, maka pemikiran lama akan ditinggalkan, ditukar dengan pemikiran yang baru dihasilkan tersebut.
Pembaharuan pemahaman dapat dilakukan apabila terpenuhi empat syarat secara kumulatif sebagai berikut.
- Ada keperluan untuk melakukan pembaharuan; misalnya saja perubahan perlu dilakukan karena ada (terjadi) perubahan adat, mungkin karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan yang menyebabkan perubahan berbagai hal di tengah masyarakat, atau menyebabkan adanya pemahaman baru yang lebih baik dibandingkan dengan mpamahaman sebelumnya.
- Ada dalil yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan; dengan kata lain ayat-ayat Al-qur’an mungkin dipahami secara baru, sehingga mungkin melakukan perubahan pemahaman atas nash.
- Perubahan tersebut dilakukan dengan metode (kaidah) yang memenuhi persyaratan metodologis; mungkin dengan menggunakan metode yang sudah ada, tetapi mungkin juga dengan menggunakan metode baru, yang dihasilkan sebagai bagian dari upaya pembaharuan tersebut. Perubahan metode akan diterima apabila memenuhi syarat menurut logika (dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan akal sehat dan nurani kemanusiaan).
- Pengubahan tersebut tidak berlawanan dengan dalil (nash) yang qath`i dilalah. Sebuah lafaz dianggap qath`i dilalah apabila mempunyai hanya satu makna karena didukung oleh nash yang lain. Maksudnya makna lafaz tersebut tidak dapat diubah karena ada nash lain yang mendukung dan menguatkannya. Pembaharuan atas lafaz yang qath`i dilalah, tidak dapat dilakukan, karena lafaz tersebut hanya mempunyai satu makna saja.
Dari segi waktu terjadinya, pembaharuan dibagi kepada dua periode. Pembaharuan yang terjadi sebelum abad kedua puluh miladiah, dan pembaharuan yang terjadi setelah abad kedua puluh miladiah.
Pembaharuan sebelum abad kedua puluh sudah dilakukan oleh banyak ulama, misalnya saja, yang sering disebut, Izz al-Din bin Abd al-Salam w. 1262 (659 H) di kalangan Syafi`iah; Ibnu Taymiyyah w. 1330 (728 H) dan Ibnu Qayyim w. 1350 (751H) di kalangan Hanabilah; Abu Ishaq Asy-Syathibi al Gharnathi w. 1388 (790 H) di kalangan Malikiah; dan Ahmad Sirhindi w. 1624 M. di kalangan Hanafiah. Pada abad kedelapan dan Sembilan belas miladiah ada tiga tokoh pembaharu yang berpengaruh besar, yaitu Syah Waliullah al-Dahlawi, (bermazhab Hanafiah, w. 1763 M) di India, Muhammad bin Abdul Wahhab (bermazhab Hanabilah, w 1792 M) di Jazirah Arabia, dan Muhammad bin Ali al-Sanusi (bermazhab Malikiah, w. 1843 M) di Libia (Maghribi). Pembaharuan yang mereka lakukan ada yang pada metode, dan ada juga yang sekaligus pada materi dan metode. Tetapi mereka masih tetap mengikatkan kepada mazhab yang ada, karena itu pembaharuan mereka tidaklah menyeluruh apalagi mendasar. Para pembaharu ini merasa adat (budaya lokal) sudah terlalu banyak masuk ke dalam fiqih, menimbulkan banyak penyimpangan (bid`ah), menyebabkan fiqih kehilangan kemurniannya, sehingga perlu diperbaharui dengan cara membuang semua pengaruh budaya lokal yang dianggap menyimpang tersebut. Tetapi ada juga yang perlu diperbaharui karena adanya perubahan adat di sesuatu tempat.Semua pendapat dan praktek yang ada diukur dan disesuaikan kembali dengan tuntunan Al-qur’an dan sunnah (praktek) yang ada pada masa Nabi Muhammad. Sebagiannya dilakukan dengan menegaskan kembali keharusan mengikuti pemahaman yang diberikan Sahabat, tetapi ada juga yang mengusulkan pemberian pemahaman baru berdasarkan perubahan pada metode pamahamannya. Menurut para pembaharu ini fiqih perlu dikembalikan kepada semangat aslinya, dan semua adat yang dianggap menimbulkan penyimpangan harus dibuang dan ditinggalkan, tetapi sebaliknya adat yang dianggap baik perlu diakomodir dan harus diterima. Upaya pembaharuan (tajdid) pada tingkatan atau model ini hampir sama dengan upaya pemurinan yang dilakukan oleh kelompok salafiah. Kedua kelompok ini menggunakan praktek (amalan) masa Nabi Muhammad dan Sahabat sebagai contoh utama. Namun tetap ada perbedaannya. Kelompok salafiah ingin mengembalikannya kepada ajaran dan praktek yang ada pada masa Nabi dalam bentuk yang sederhana, yang relatif tanpa sistem. Sedang kelompok tajdidiah periode pertama ini, mengembalikannya kepada ajaran dan praktek pada masa Nabi dan Sahabat, tetapi melakukannya melalui metode yang relatif jelas dan terukur, serta mempertimbangkan adat sesetempat dan setelah itu menyusunnya dalam sebuah system yang relatif padu.
Adapun pembaharuan periode kedua, yang dilakukan sejak akhir abad kesembilan belas miladiah, atau lebih tepat di awal abad keduapuluh miladiah, cenderung lebih mendasar dan lebih menyeluruh. Para pembaharu periode kedua, cenderung mendorong agar para ulama memikirkan ulang seluruh ajaran agama (menafsirkan ulang Al-qur’an dan sunnah) dalam upaya lebih menyesuaikannya dengan keperluan masa kini. Anjuran ini mereka kemukakan karena ada keyakinan bahwa perubahan adat atau budaya yang terjadi sekarang ini, relatif sangat mendasar dan menyeluruh, setelah adanya kemajuan ilmu dan teknologi, yang melahirkan era industri, dan sekarang ini sedang beralih ke era informasi dan bio teknologi. Karena perubahan yang mendasar dan menyeluruh ini, hasil pemikiran masa lalu seperti ditemukan dalam fiqih (bahkan semua hasil ijtihad ulama masa lalu, termasuk ilmu kalam) yang masih kita pakai sekarang, tidak mampu lagi memenuhi keperluan masyarakat. Dapat ditambahkan ketidak sesuaian tersebut tidak saja pada hasil pemikiran (ketentuan fiqih yang ada dalam berbagai mazhab, atau himpunan pendapat Sahabat dalam kitab-kitab), tetapi juga pada metode berpikirnya (metode istinbath, ushul fiqihnya). Ushul fiqih yang ada sekarang dianggap sudah terlalu sederhana, sekiranya dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh logika. Dengan demikian metode berpikir inipun mau tidak mau harus diubah, dikembangkan dan disesuaikan dengan keadaan dan keperluan masa kini.
Keyakinan bahwa ketentuan yang ada dalam fiqih dan ushul fiqih (bahkan semua ilmu-ilmu ke-Islaman) yang dihasilkan pada masa lalu, perlu diubah dan disesuaikan dengan keadaan, keperluan dan kemajuan ilmu dan teknologi, muncul dari kesadaran umum masyarakat, tentang terjadinya perubahan yang relatif mendasar dan menyeluruh antara masa lalu (ketika wahyu turun dan imam mazhab melakukan ijtihad) dengan masa sekarang (setelah kehadiran ilmu dan teknologi). Menurut pengikut dan penganjur pola tajdidiah periode kedua, hasil pemikiran dan juga metode yang ada dalam pola salafiah dan mazhabiah tidak mampu lagi memecahkan berbagai kebutuhan masa kini, karena banyak masalah yang muncul pada masa sekarang tidak ada dalam budaya masa lalu, bahkan tidak terbayangkan pada masa itu. Para ulama pendukung tajdidiah berkeyakinan, untuk menjaga agar fiqih dapat mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi di satu pihak, serta dapat memberikan maslahat dan dapat memenuhi keperluan umat di pihak yang lain, maka fiqih harus dikembangkan dan disempurnakan. Untuk pengembangan ini menurut pendukung pola tajdidiah, ulama harus memilih pola tajdidiah betapapun berat dan sukarnya, karena tidak ada pilihan lain.
Adanya perbedaan mendasar antara keadaan masa Sahabat dan imam mazhab dengan keadaan masa sekarang, begitu juga perbedaan antara adat dalam masyarakat Arab dengan adat dalam berbagai masyarakat muslim di berbagai belahan dunia, baru diketahui dan Bru dapat dijelaskan secara ilmiah adalah setelah adanya kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu modern seperti antropologi dan sosiologi meneliti, membahas dan menjelaskan berbagai perbedaan tersebut. Begitu juga pengetahuan bahwa pemahaman masa Sahabat dahulu mereka lakukan berdasar internalisasi dan sosialisasi, dan karena itu tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah, baru dapat dijelaskan secara ilmiah pada masa sekarang setelah orang-orang mempelajari psikologi. Begitu juga keyakinan tentang adanya metode lain untuk memahami nash yang relatif lebih mudah, lebih baik dan lebih dapat dipertanggungjawabkan dibanding dengan model internalisasi, yang penulis sebut sebagai model pemahaman akademik ilmiah, baru muncul pada masa sekarang, sebagai akumulasi atas berbagai temuan ilmu pengetahuan.[7]
Untuk mencapai tujuan itu, pengikut pola tajdidiah periode sekarang berupaya menafsirkan nash (ajaran Islam) sebagai sebuah sistem yang padu sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Fiqih diupayakan menjadi sebuah himpunan peraturan yang padu, yang bukan sekedar himpunan atas peraturan-peraturan yang bersifat juz`iyyah. Untuk itu pertama sekali diupayakan melahirkan metode berpikir yang lebih sistematis dan lebih padu. Model berpikir yang dihasilkan oleh logika masa kini, yang oleh Noeng Muhajir sudah diklasterkan menjadi lebih sepuluh buah, seperti pola pikir genetik, pola pikir sistematisasi, pola pikir statik dan dinamik, pola pikir pernyataan realitas dan pola pikir perwujudan realitas, akan diupayakan untuk diakomodasi dalam ushul fiqih baru yang akan dihasilkan tersebut.[8] Pola pikir bayani, burhani dan irfani seperti dikemukakan oleh `Abid al-Jabiri juga akan ditampung dan diupayakan menjadikannya sebagai bagian dari ushul fiqih baru yang akan disusun (dibuat) itu. Sedang mengenai ijtihad untuk merumuskan hukum atau definisi atas peruatan hukum, mereka menawarkan ijtihad bertingkat. Pada tingkat pertama dilakukan ijtihad untuk menghasilkan apa yang dianggap sebagai nilai-nilai menurut Al-qur’an dan hadis. Setelah itu diupayakan pula merumuskan apa yang menjadi prinsip-prinsip (dan kalau mungkin juga hikmah-hikmah). Baru setelah ini dilakukan ijtihad untuk menetapkan (menemukan, memikirkan) hukum atas suatu masalah,atau merumuskan definisi atas sesuatu perbuatan. Nilai dan prinsip sebagai hasil ijtihad tingkat pertama dan kedua, akan digunakan sebagai pedoman dan pemandu ketika mengijtihadkan hukum atas suatu perbuatan (kasus) atau definisi dari sesuatu perbuatan (kasus). Dengan menggunakan ijtihad bertingkat ini, maka hasil ijtihad diharapakan akan tetap berada di dalam lingkup nilai dan prinsip yang islami, bukan merupakan pendapat yang menyempal, liar atau semena-mena, apalagi menyimpang dari semangat Al-qur’an. Untuk ini penganjur pola tajdidiah berupaya memanfaatkan secara maksimal hasil yang dicapai oleh berbagai cabang ilmu pengetahuan modern, termasuk logika. Hasil dan capaian ilmu pengetahuan modern tersebut akan digunakan dalam upaya merumuskan prinsip-prinsip sebagai hasil pemikiran tingkat pertama, serta dalam penentuan hukum atas sesuatu kasus dan atau merumuskan definisi dari sesuatu perbuatan sebagai pemikiran tingkat kedua.
Dengan demikian ada tiga ciri utama pemikiran tajdidiah, pertama tidak terikat bahkan berusaha keluar dari ketentuan yang ada, baik ketentuan dalam pola salafi ataupun mazhabi; yang kedua, berupaya memanfaatkan hasil dan capaian ilmu pengetahuan dalam upaya menghasilkan aturan fiqih baru tersebut; dan yang ketiga berupaya melakukan panafsiran bertingkat, menentukan terlebih dahulu prinsip-prinsip dari ayat Al-qur’an dan sunnah, dan baru setelah itu menyusun ketentuan fiqihnya.
Sekiranya dikritisi, maka pemikiran (manhaj) tajdidiah mempunyai kelebihan dan kekurangan, diantaranya sebagai berikut. Kelebihannya, pola tajdidiah diharapkan mampu menjadikan ajaran Islam (fiqih) lebih sesuai dengan keperluan umat Islam masa kini. Dengan pemahaman Islam yang berpola tajdidiah umat Islam diharapkan tidak akan teralienasi dari lingkungannya dan juga tidak perlu menempuh jalan sekularisasi, karena mereka akan menemukan jalan keluar untuk berbagai persoalan yang muncul akibat kemajuan ilmu dan teknologi. Mereka tidak akan bingung dan gamang ketika harus bersaing atau bersanding dalam berbagai aspek kehidupan yang muncul akibat kehadiran pemikiran modern (yang sekuler), terutama menghadapi kegiatan bisnis (perdagangan global) masyarakat dunia sekarang. Dengan menggunakan pola tajdidiah, umat Islam diharapkan akan mempunyai jawaban yang lebih memuaskan atas berbagai kegiatan bisnis yang ada sekarang, baik ketika kegiatan itu ditolak (diharamkan) ataupun ketika kegiatan itu diterima (dimubahkan). Seperti telah disebutkan untuk dapat memberikan jawaban yang lebih memuaskan, maka pemanfaatan capaian ilmu hukum serta ilmu ekonomi “modern” dan ilmu-ilmu lainnya dalam penyusunan fiqih baru tersebut, merupakan keniscayaan yang tidak dapat diabaikan.
Kekurangannya, pola ini tidak mempunyai preseden dari masa lalu, sehingga cenderung akan dicurigai dan bahkan ditolak oleh sebagian umat Islam karena dianggap tersusupi dan tercemar oleh budaya asing yang bertentangan dengan Islam. Lebih dari itu pengikut pola tajdidiah belum berhasil mewujudkan sebuah pola atau model pemikiran yang padu seperti yang mereka harapkan dan upayakan. Dengan kata lain, walaupun hasrat untuk mengikuti pola tajdidiah sudah disampaikan oleh Afghani, Abduh dan Ameer Ali sejak satu abad yang lalu, dan sekarang ini disuarakan oleh lebih banyak ulama pembaharu seperti Fazlurrahman, Abed al-Jabiri, Khaled Aboe el Fadhl, dan yang lainnya, bentuk kongkrit dari pola tajdidiah dan hasil pemikirannya masih belum lahir dalam bentuk yang siap pakai. Sampai sekarang para ulama pengusung pola tajdidiah masih dalam tingkat mencari, menyusun, menyempurnakan dan memperbaiki berbagai gagasan yang sudah ada. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, pola tajdidiah yang akademik, ilmiah, sistematis dan menyeluruh seperti yang selama ini diharapkan, akan dapat dihasilkan oleh para pemikir muslim yang serius dan peduli untuk itu.
Dengan uraian di atas akan terlihat bahwa salafiah tidak sama dengan tajdidiah. Para pengikut model tajdidiah berupaya memahami dan menafsirkan Al-qur’an untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan cara mempertimbangkan adat dan budaya umat Islam setempat di satu sisi, dan dengan memanfaatkan hasil dan capaian ilmu pengetahuan moderndi sisi yang lain. Sebaliknya pengikut model salafiah pada dasarnya mengacu ke masa lalu, mencari dan memilih praktek pada zaman Nabi dan Sahabat untuk memecahkan problem yang muncul pada masa sekarang. Secara umum pengikut salafiah cenderung tidak mau memanfaatkan hasil dan capaian ilmu pengetahuan modern untuk memecahkan masalah umat, walaupun akan dilakukan di bawah sinaran Al-qur’an dan sunnah . Pola Salafiah pada biasanya seperti telah disebutkan, akan berusaha menyederhanakan masalah, tidak merasa perlu berpikir komprehensif apalagi melahirkan sebuah sistem yang padu.
Pada masa lalu upaya untuk kembali kepada Al-qur’an dan sunnah untuk meluruskan pemikiran yang dianggap sudah menyimpang, ataupun mencari pemikiran baru sebagai alternatif atas ketentuan fiqih yang sudah ada dapat dianggap sebagai tajdidiah, karena perubahan adat dan budaya–sejak masa Sahabat sampai ke masa penjajahan Barat atas dunia Islam boleh dikatakan tidak terjadi secara mendasar apalagi radikal. Tetapi pada masa sekarang perubahan telah terjadi secara relatif radikal dan mendasar. Karena itukembali ke Al-qur’an dan sunnah tanpa mempertimbangkan adat yang berubah dan lebih dari itu tanpa mempertimbangkan dan memanfaatkan hasil ilmu pengetahuan, akan dianggap sebagai bagian dari berpikir mengikuti pola salafiah bukan lagi tajdidiah.[9]
Muhammadiyah, seperti terlihat pada awal tulisan ini kemungkinan sekali belum membedakan secara tajam antara salafiah dengan tajdidiah. Jangan-jangan apa yang selama ini dianggap tajdidiah sebetulnya adalah salafiah; apa yang kita anggap sebagai berkemajuan dan berorientasi ke masa depan, sebetulnya adalah kejumudan dan kebekuan, karena masih berorientasi ke masa lalu. Kegiatan berpikir yang kita lakukan masih berorientasi kepada bagaimana kita mengikuti amalan Rasulullah dan Sahabat persis seperti yang mereka kerjakan pada abad ke tujuh hijriah (katakanlah secara harfiah ataupun sekedar mengikuti formalitasnya). Bukan berupaya memahami dan menafsirkan untuk memperoleh dan menjaga keberlangsungan nilai dan manfaatnya, dan setelah itu baru mengamalkannya untuk memenuhi keperluan masa sekarang. Boleh dikatakan kita belum secara sungguh-sungguh mempertimbangkan nilai yang ingin dicapai oleh Al-qur’an melalui ketentuan dan aturan yang disampaikannya, di satu pihak, dan di pihak lain kita juga belum mempertimbangkan secara sungguh-sungguh dan mendalam keperluan nyata masyarakat muslim masa sekarang. Para ulama kita juga kelihatannya belum mempelajari dengan baik perbedaan keadaan lingkungan dan budaya yang ada pada masa Nabi dengan yang ada pada masa sekarang. Begitu juga para ulama masa sekarang cenderung belum mempertimbangkan secara sungguh-sungguh, kemajuan dan hasil ilmu pengetahuan serta teknologi yang telah melahirkan zaman industri dan zaman informasi, ketika berupaya memahami dan manafsirkan ayat-ayat dan hadis Rasulullah. Karena itu upaya tajdidiah masih memerlukan kerja keras dan kesungguhan agar dapat memberikan hasil dalam bentuk fiqih yang relatif menyeluruh, yang dapat digunakan dalam kehidupan nyata dalam waktu yang tidak terlalu lama ke depan nanti.
Sebagai penutup, dapat dikatakan pengetahuan dan kesadaran tentang telah terjadinya perubahan penting dan mendasar dalam masyarakat muslim karena adanya kemajuan ilmu dan teknologi sudah semakin meluas dan merata. Kesadaran tentang adanya perbedaan budaya dalam berbagai masyarakat muslim di berbagai benua pun semakin disadari dan diyakini. Karena itu keyakinan dan upaya untuk mengembangkan, menyempurnakan dan bahkan mengganti fiqih yang ada sekarang dengan fiqih baru, juga semakin meluas dan merata. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan oleh para ulama dan sarjana yang peduli. Tetapi usaha tersebut belum ada yang sudah berhasil dalam arti sudah dapat digunakan secara praktis di tengha masyarakat muslim. Karena itu diskusi yang sungguh-sungguh, yang mencerdaskan dan bertujuan untuk membangun harus semakin digalakkan dan perlu dilakukan secara berkala, baik pada tingkat lokal, nasional ataupun ntrnasional. Kritik yang diajukan, betapapun pedas dan tajamnya, selama disampaikan dengan santun dan dengan tujuan untuk membangun, harus diterima dan dipertimbangkan, karena hanya dengan berdiskusi dan saling bertukar pikiranlah kedekatan hati dan saling memahami dapat terjadi.
Salah satu buku fiqih yang sudah ditulis secara lengkap, yang berupaya mengikuti model tajdidiah, walaupun belum sempurna, menurut pengamatan penulis adalah kitab Fiqh al-Sunnah karangan Sayyid Sabiq. Penulis menganggap kitab ini berpola tajdidiah, karena tidak lagi terikat dengan mazhab. Namun kitab ini masih menyebutkan pendapat yang ada dalam mazhab, tetapi tidak mengikatkan diri kepada salah satu dari pendapat mazhab tersebut. Penyebutan pendapat ulama masa lalu, baik dari kalangan mazhab ataupun Sahabat, menurut penulis sangat perlu dilakukan agar pembaca dapat mengetahui adanya ketersambungan ataupun keterputusan yang dilakukan oleh pengarang. Namun dari segi metode, kitab ini boleh dikatakan belum melakukan tajdid, karena masih menggunakan ushul fiqih yang sudah ada sebagai metode. Jadi dari segi metode masih mengikuti model mazhabiah. Karena itu pembaharuan yang dilakukannya barulah pada pendapat fiqih dalam arti sudah berupaya untuk keluar dari pendapat mazhab, tetapi belum pada metodenya, sehingga belum melakukan tajdid secara sungguh-sungguh.
Buku fiqih lain yang dapat dianggap sudah berupaya juga mengikuti model tajdidiah walaupun belum sempurna juga, adalah buku Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, karangan Wahbah al-Zuhaili. Berbeda dengan buku Sayyid Sabiq, buku ini secara umum masih mengutip ketentuan yang ada dalam mazhab dalam bentuk perbandingan antar mazhab. Begitu juga metode yang digunakan masih mengikuti ushul fiqih yang disusun oleh ulama mazhab. Dengan demikian, buku ini masih termasuk ke dalam model mazhabiah, bukan tajdidiah ataupun salafiah. Tetapi berbeda dengan buku yang mengiktui model mazhabiah secara penuh, beliau memasukkan pembahasan penting yang menjadi ciri dari fiqih model tajdidiah, yaitu uraian tentang prinsip-prinsip (mabadi’, nazhariyyat) fiqih. Lebih dari itu beliau juga memasukkan banyak materi (bab) baru yang sebelumnya tidak menjadi pembahasan fiqih, atau paling kurang tidak menjadi bagian integral dari kitab fiqih. Dengan demikian, sekiranya dilihat dari dua aspek ini, kitab di atas dapat dianggap sudah mengikuti pola tajdidiah secara terbatas. Dua contoh ini barangkali dapat menjadi petunjuk bahwa upaya menulis kitab fiqih mengikuti model tajdidiah seperti dipilih Muhammadiyah masih memerlukan kerja keras secara berkesinambungan. Untuk itu tentu perlu stamina dan energi yang prima secara berkelanjutan, agar tidak kehabisan nafas di tengah perjalanan. Motor penggerak dan pengawal untuk kegiatan ini adalah Majelis Tarjih dan Tajdid, yang tentu harus dibantu oleh semua perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah.
Akhirnya sebagai penutup, sekiranya dituliskan di dalam taswir, perbedaan salafiah, mazhabiah dan tajdidiah dapat disebutkan sebagai berikut.
| No | ASPEK | SALAFIAH | MAZHABIAH | TAJDIDIAH |
| 1 | Dasar metode | Internalisasi, | internalisasi, | akademik ilmiah |
| 2 | Metode | sederhana, bebas & semena-mena | Lugawiah | Ta`liliah, istislahiah, burhani |
| 3 | Orientasi | Masa lalu, Sahabat | Masa lalu, mazhab | Masa kini dan masa depan |
| 4 | Cakupan isi | Parsial praktis | Parsial, praktis, sistematis | Padu, menyeluruh sistematis |
| 5 | Jumlah kebenaran | Tunggal, tarjih | Tunggal, tarjih | Beragam, tanawwu` |
| 6 | Sistematika | Sederhana | Tertutup | Terbuka |
| 7 | Penghargaan atas pendapat Sahabat | Bagian dari sunnah Rasul | Bagian dari sunnah Rasul | Sama dengan ijtihad lain |
| 8 | Hubungan dengan ilmu &teknologi | Menolak ilmu | Menerima terbatas | Menerima dan memanfaatkan |
| 9 | Logika yang dipakai | Subjektif, kata hati, pikiran logis | Logika formal Aristoteles | Logika modern (deduktif, induktif, reflektif) |
Semoga tulisan ini ada manfaatnya, dan semoga Allah memberi kelapangan kepada penulis, sehingga dapat melanjutkan dengan contoh-contoh tentang berpikir salafiah, mazhabiah dan tajdidiah dalam beberapa kasus yang sekarang ini sedang hangat diperdebatkan di kalangan Muhammadiyah secara khusus dan kaum muslimin secara lebih umum. Kepada Allah penulis berserah diri, kepada Nya dipersembahkan bakti dan kepada Nya pula dimohon hidayah penerang hati dan penyejuk hati. Wallah a`lam bi-s-shawab. Amin.
Banda Aceh, Juni 2015 M, bersamaan dengan Sya`ban 1436 H.
Catatan Akhir:
[1] Haedar Nasir, Muhammadiyah Gerakan Pembaruan, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, cet. 1, 2010, hlm. 1.
[2]Haedar Nasir, hlm. 6.
[3]Sebagai contoh, sebagian ulama di Arab Saudi tanpa alasan yang jelas dan logis, menyatakan haram bagi orang perempuan untuk mengemudikan mobil di jalan raya, baik siang ataupun malam hari.
[4] Penjelasan tentang pola mazhabiah (dalam membandingkannya dengan pola salafiah) relatif hanya sesuai dengan perkembangan fiqih, tidak sesuai dengan perkembangan ilmu kalam dan tarikat (tasauf). Mazhab (aliran) dalam ilmu kalam dan tarikat bukanlah sistematisasi dan reduksi atas pendapat yang ada pada masa Sahabat. Boleh dikatakan para Sahabat tidak meninggalkan pendapat di bidang kalam dan tarekat seperti yang mereka tinggalkan di bidang fqih. Mazhab kalam dan tarekat secara umum disusun berdasarkan pikiran (pemahaman) pendirinya atas Al-qur’an dan sunnah, dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat mereka capai pada masa mereka sebagai alat analisis (misalnya bahasa, adat istiadat, ajaran agama, budaya dan ilmu penggetahuan yang ada). Pikiran ini mereka susun di samping untuk menjelaskan ajaran tauhid kepada umat, mereka susun juga untuk melindungi Islam dari tantangan “luar” (filsafat, mistik dan ajaran agama bukan Islam) pada masa mereka masing-masing. Dengan demikian, berbeda dengan fiqih, mazhab kalam dan tarekat secara umum tidak mempunyai akar dan pertautan langsung dengan pendapat yang ada pada masa Sahabat. Mazhab yang ada di bidang kalam (muktazilah, asy`ariah, dan maturidiah) bukanlah himpunan ataupun sistematisasi atas pendapat-sahabat Sahabat di bidang kalam. Begitu juga ajaran kalam yang diakui sebagai ajaran salaf (salafiah), bukanlah merupakan himpunan ataupun pilihan dari pendapat-pendapat yang diberikan oleh para Sahabat. Ajaran tersebut merupakan mazhab kalam yang disusun oleh para ulama yang datang belakangan, yang menamakan diri sebagai pengikut salaf (salafiah) seperti Ibnu Taymiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab (Wahabiah).
Perlu ditambahkan, ahlussunnah wal jama`ah bukanlah sebuah istilah yang tepat makna. Istilah ini sering sekali digunakan secara salah untuk kepentingan kelompok, misalnya saja untuk membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Istilah ini bukanlah nama untuk satu kelompok tertentu secara khusus. Ketika lahir, istilah ini digunakan untuk menunjuk mayoritas umat yang tidak menyempal karena adanya perbedaan pandangan atau kepentingan politik. Dalam kemelut perebutan kekuasaan setelah Usman bin Affan terbunuh, kelompok yang membela Ali sebagai khalifah yang sah menamakan dirinya sebagai syi`ah (syi`ah Ali, partai Ali). Sedang kelompok yang menolak kekhalifahan Ali dan juga kekuasaan Mu`awiah menamakan dirinya khawarij (kelompok yang keluar, yang memisahkan diri). Dengan demikian mayoritas umat, yang berada di luar dua kelompok di atas (tidak mau menjadi syi`ah atau khawarij) dinamakan ahlussunnah wal jamaah. Dalam perjalanan sejarah, kelompok-kelompok tertentu di luar dua kelompok di atas sering sekali mengaku, hanya merekalah yang berhak menyandang sebutan ahlussunnah wal jama`ah. Sebagian pengikut aliran kalam asy`ariahmisalnya, menganggap hanya aliran asy`ariah (nisbah kepada Imam Abu-l Hasan al-Asy`ari, wafat936 M atau 324 H) dan aliran maturidiah (nisbah kepada Imam Abu Mansur al-Maturidi, wafat tahun 944 M atau 333 H)sajalah yang merupakan representasi dari ahlussunnah wal jamaah. Sedang aliran lainnya, dianggap sebagai aliran menyempal, sehingga tidak layak untuk menyandang sebutan tersebut.
[5]Beberapa buku menceritkan bahwa mazhab Syi`ah tidak selamanya mendapat tempat yang khusus. Kadang-kadang ada penguasa yang melarang mereka melakukan jamaah secara resmi dan terbuka, sehingga jamaah resmi yang selalu ada sampai saat dibubarkan oleh ulpenguasa Saudi (wahabiah) hanya tiga jamaah saja.
[6]Mihrab untuk imam bermazhab Syafi`i terletak dekat sumur Zamzam dan jamaahnya mengelompok di belakang beliau membentuk seperempat lingkaran di sekitar tempat ini. Pengikut mazhab Syafi`iah sering membanggakan diri karena mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat terletak dekat dengan mihrab imam mereka. Mereka dianjurkan masuk melalui Bab Salam, karena pintu inilah yang terletak persis di belakang mereka. Mihrab untuk imam bermazhab Hanafi terletak dekat Rukun Iraqi, salah satu ujung Hijir Ismail dan jamaahnya membentuk seperempat lingkaran di sekitar tempat ini. Mereka dianjurkan masuk melalui Bab Fatah, karena pintu ini terletak di belakang tempat mereka. Mihrab untuk imam bermazhab Maliki terletak dekat rukun Syami, ujung Hijir Ismail yang sebelah lagi, dan jamaahnya membentuk seperempat lingkaran di sekitar tempat itu. Mereka dianjurkan masuk melalui Bab Malik karena pintu inilah yang terletak di belakang tempat mereka. Buku yang penulis baca tidak menyebutkan tempat mihrab untuk imam bagi saudara-saudara kita yang bermazhab Syi`ah, mungkin seperti telah disebutkan karena mereka tidak diberi kesempatan secara permanen untuk mempunyai mihrab sendiri.
Beberapa teman yang pernah mengunjungi Masjid Aqsha, menyampaikan kepada penulis bahwa di sana, shalat fardhu dengan empat imam dan empat jamaah masih berlangsung sampai saat ini.
Dapat ditambahkan, ketika para tentera yang berasal dari kelompok budak-budak di Mesir dan Suriah merebut kekuasaan dan membentuk dinasti sendiri, yang berkuasa dari 1250-1517, mereka melakukan sebuah perubahan penting di bidang fiqih. Untuk medapat dukungan dari ulama dan rakyat atas pemerintahan mereka yang tidak sah (karena mereka keturunan budak, bukan keturunan Qureisy), mereka membentuk pengadilan berdasarkan mazhab. Kalau sebelumnya hanya ada satu pengadilan resmi, mengikut mazhab para penguasa di seluruh wilayah kekhalifahan, maka dinasti ini membentuk empat pengadilan sesuai dengan empat mazhab sunni di semua wilayah kekuasaan mereka. Akibat kebijakan ini masyarakat dikelompokkan menjadi empat kelompok secara relatif tegas dan permanen. Masjid menjadi empat buah di setiap pemukiman, sesuai dengan mazhab. Masing-masing pengikut mazhab mencari masjidnya sendiri dan cenderung tidak akan eprgi ke masjid yang bermazhab lain. Kalau terjadi sebuah perbuatan hukum yang melibatkan orang dari mazhab yang berbeda (misalnya pernikahan dan jual beli), maka mereka harus bersepakat terlebih dahulu, ke pengadilan bermazhab apa akan dibawa sekiranya nanti terjadi pertengkaran diantara mereka. Jadi pengadilan antar warga yang berbeda mazhab pada waktu itu hampir sama dengan pengadilan intergentil (antar tata hukum) pada masa penjajahan Belanda dahulu, yang sangat dikecam karena memecah belah penduduk. Sisa kebijakan ini masih terlihat pada pembagian jurusan pada program S1 Fakultas Syari`ah Universitas Al-Azhar, yang dilakukan berdasar mazhab, Hanafiah, Malikiah dan Syafi`iah (bersama-sama dengan Hanabilah). Namun perlu dijelaskan, pada program pasacasarjana pembagian tidak lagi berdasar mazhab, tetapi berdasar bidang: ushul fiqih, muqaranat al-mazahib, dan siyasah syar`iyyah.
[7]Pada masa Sahabat ilmu-ilmu ke-Islaman masih belum lahir (belum disusun oleh para ulama). Jadi Sahabat tidak mempunyai pilihan selain dari melakukan penalaran melalui model internalisasi. Ilmu nahu (tata bahasa Bahasa Arab) misalnya, mulai diupayakan penyusunannya oleh oleh Abu-l Aswad ad-Duwali (wafat 69 H), atas usulan Khalifah Ali bin Abi Thalib (wafat 40 H). Ushul fiqih sebagai ilmu tentang metode penalaran (penafsiran atas Al-qur’an untuk kepentingan fiqih) pertama sekali disusun oleh Imam al-Syafi`i (wafat 204 H) dan baru dianggap sempurna dalam buku-buku yang ditulis oleh ulama pada abad ketujuh hijriah, seperti Fakhrud-Din Ar-Razi,pengarang kitab Al-Mahshul fi `Ilm-il Ushul, yang wafat tahun 606 H (1209 M).
Perbedaan dan perbandingan antara model internalisasi dan sosialisasi dengan model akademik ilmiah formal, barangkali dapat dilihat pada pengajaran bahasa. Melalui model internaslisasi dan sosialisasi para orang tua (keluarga dan masyarakat) mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anaknya, sehingga mereka dapat menggunakan bahasa tersebut secara relatif baik. Tetapi ketika anak Indonesia belajar bahasa asing misalnya Bahasa Arab atau Inggeris, kebanyakan (bahkan semua) mereka tidak menggunakan model internaslisasi dan sosialisasi karena disekitar mereka tidak ada orang yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa sehari-hari. Mereka harus mempelajarinya secara formal akademik, dengan mempelajari tatabahasanya, belajar melafalkan kata-katanya, serta menghafal kosa katanya. Selanjutnya untuk mejadi seorang yang ahli (menguasai pengetahuan tentang bahasa tersebut secara ilmiah, professional, bukan amatiran, baik bahasa ibu ataupun bahasa asing) seseorang harus mempelajarinya secara akademik ilmiah, tidak mungkin (sangat sukar) melalui cara internaslisasi dan sosialisasi.
Beberapa penulis dan sarjana mengatakan, pengajaran dan pewarisan nilai akan sangat baik sekiranya dilakukan melalui cara internalisasi dan sosialisasi, misalnya saja oleh keluarga kepada anak-anak sejak mereka kecil sampai dewasa. Adapun pengajaran dan pewarisan ilmu pengetahuan apalagi pengembangannya tidak dianggap cukup melalui model internalisasi dan sosialisasi. Pengembangan ilmu dan teknolgi, di bidang apapun ilmu dan teknologi itu, harus dilakukan melalui pengajaran formal akademik. Menurut para ulama dan cendekiawan, pengajaran tersebut akan menjadi lebih baik, (efektif dan efisien) sekiranya dirancang dan dilaksanakan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah akademik.
[8]Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian, Rake Sarasin Yogyakarta, Edisi 6, 2011, hlm. 82.
[9] Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam Kata Pengantar cetakan keempat buku yang beliau susun,Pedoman Shalat, Bulan Bintang, Jakarta, 1959, mengatakan bahwa tujuan penulisan buku antara lain adalah, supaya tiap-tiap muslim dapat mendirikan shalat, bukan sekedar memperlihatkan rupa shalat. Lantaran demikian kami menitik-beratkan uraian pada kesempurnaan shalat di dalam praktek secara praktis. Kami berpendapat, yang penting diajarkan adalah cara melaksanakan shalat sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah Saw., bukan mengetahui ini rukun, ini syarat. Karena itu dalam menerangkan aqwal dan af`al shalat kami tidak menandaskan ini rukun, ini syarat, ini sunat ab`adh, ini sunat hay’ah sebagai yang dibiasakan oleh para guru pengajar shalat di negeri kita. Selanjutnya Hasbi berkata, namun setelah penerbitan pertama tersebar, ada pembaca yang menghendaki supaya kami menerangkan mana yang menjadi rukun, mana yang menjadi syarat, mana yang sunat dan mana yang makruh. Untuk itu kami menambahkan bab baru guna menjelaskan hal-hal yang diharapkan pembaca tersebut.
Dari pernyataan ini dapat disimpulkan, pada awalnya Hasbi ingin mengikuti kecenderungan para pengikut model salafiah. Tetapi cara ini beliau tinggalkan pada cetakan berikutnya, karena ada pembaca yang meminta agar beliau menjelaskan bimbingan dan tuntunan Nabi tentang shalat tersebut dengan menggunakan istilah yang lazim dipakai, yaitu istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum taklifi dan hukum wadh`i. Dengan kata lain pembaca meminta agar beliau mengikuti pola mazhabiah, agar para pembaca lebih mudah memahaminya. Pengalaman ini barangkali dapat memberi petunjuk bahwa menulis fiqih mengikuti pola salafiah (tanpa menggunakan kategori atau sistematika) akan menimbulkan kesulitan, paling kurang pada sebagian pembaca.
Di pihak lain, dalam buku yang penulis gunakan (cetakan 23, 1994), beliau mengutip hadis dan menjelaskan isinya (hukumnya) menurut pemahamnya sendiri, yang kadang-kadang keluar dari ketentuan mazhab dan ketentuan yang lazim di kalangan salafiah. Dengan demikian beliau sudah mengikuti model tajdidiah, walaupun masih dalam pendapat fiqih belum pada metodenya. Beliau juga memasukkan pembahasan baru yang tidak lazim ditemukan dalam buku-buku fiqih lama, seperti Kedudukan Shalat dalam Rangka Pembianan Iman, Martabat Shalat diantara Martabat Ubudiyah, Kedudukan Khusyu`, Ikhlash, Takut dan Hadir Hati di dalam Shalatdan Hikmat-Hikmat dan Rahasia-Rahasia yang Dikadung Shalat. Pembahasan yang relatif baru ini secara tidak langsung sudah berkaitan dengan nilai, prinsip dan hikmah yang menurut pengikut model tajdidiah harus dimasukkan sebagai bagian dari pembahasan fiqih.
Buku ini barangkali dapat menjadi contoh tentang adanya tolak tarik dalam diri penulis, antara mengikuti model salafiah, mazhabiah dan tajdidiah.
*) Makalah ditulis untuk Pengajian Majelis Tarjih PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Makassar, Ahad 14 Juni 2015, bertepatan 27 Sya`ban 1436.
sumber: alyasaabubakar.com
Tags: FiqihMuhammadiyah